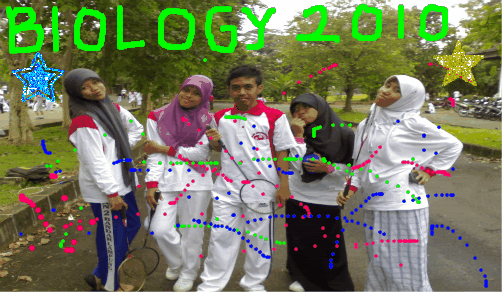BAB II. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Bimbingan Konseling
Pengertian Bimbingan
Kegiatan bimbingan dan konseling dapat mencapai hasil yang efektif bilamana dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program bimbingan berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling. Winkel dalam Soetjipto dan Kosasi (2009: 91) menjelaskan bahwa program bimbingan merupakan suatu rangakaian kegiatan terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode waktu tertentu.
Menurut pendapat Hotch dan Costor yang dikutip oleh Gipson dan Mitcheell (1981) program yang memberikan layanan khusus yang dimaksudkan untuk membantu individu dalam mengadakan penyesuaian diri. Program bimbingan itu menyangkut dua faktor, yaitu: (1) faktor pelaksana atau orang yang akan memberikan bimbingan dan (2) faktor-faktor yang berkaitan dengan perlengkapan, metode, bentuk layanan siswa-siswa, dan sebagainya, yang mempunyai kaitan dengan kegiatan bimbingan. (Abu Ahmadi dalam Soetjipto dan Kosasi, 2009: 91).
Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dari seorang yang ahli, namun tidak sesederhana itu untuk memahami pengertian dari bimbingan. Pengertian tetang bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya sejak awal abad ke-20, yang diprakarsai oleh Frank Parson pada tahun 1908. Sejak itu muncul rumusan tetang bimbingan sesuai dengan perkembangan pelayanan bimbingan, sebagai suatu pekerjaan yang khas yang ditekuni oleh para peminat dan ahlinya. Pengertian bimbingan yang dikemukakan oleh para ahli memberikan pengertian yang saling melengkapi satu sama lain.
Banyak sekali pendapat para ahli mengenai pengertian bimbingan. Frank Parson merumuskan pengertian bimbingan dalam beberapa aspek yakni bimbingan diberikan kepada individu untuk memasuki suatu jabatan dan mencapai kemajuan dalam jabatan. Pengertian ini masih sangat spesifik yang berorientasi karir. “Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih,mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan dan mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya” (Frank Parson ,1951).
“Bimbingan membantu individu untuk lebih mengenali berbagai informasi tentang dirinya sendiri” (Chiskolm,1959). Bimbingan membantu individu memahami dirinya sendiri, pengertian ini menitik beratkan pada pemahaman terhadap potensi diri yang dimiliki.
“Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu” (Bernard & Fullmer ,1969). Bimbingan dilakukan untuk meningkatakan pewujudan diri individu. Dapat dipahami bahwa bimbingan membantu individu untuk mengaktualisasikan diri dengan lingkungannya.
“Bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan proses belajar yang sistematik” (Mathewson,1969). Mathewson mengemukakan bimbingan sebagai pendidikan dan pengembangan yang menekankan pada proses belajar. Pengertian ini menekankan bimbingan sebagai bentuk pendidikan dan pengembangan diri, tujuan yang diinginkan diperoleh melalui proses belajar.
M. Surya (1988:12) berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian atau layanan bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.
Bimbingan ialah penolong individu agar dapat mengenal dirinya dan supaya individu itu dapat mengenal serta dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kehidupannya (Oemar Hamalik, 2000:193).
Bimbingan adalah suatu proses yang terus-menerus untuk membantu perkembangan individu dalam rangka mengembangkan kemampuannya secara maksimal untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat (Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 1990:11).
Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah inti sari bahwa bimbingan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin, dan membantu siswa agar memahami dirinya (self understanding), menerima dirinya (self acceptance), mengarahkan dirinya (self direction), dan merealisasikan dirinya (self realization).
Pengertian Konseling
Istilah konseling sering diartikan sebagai penyuluhan, walaupun sebenarnya kurang tepat. Untuk menekankan kekhususannya digunakan istilah bimbingan dan konseling. Kegiatan-kegiatan konseling mempunyai ciri sebagai berikut:
1. Pada umumnya dilaksanakan secara individua\
2. Pada umumnya dilaksanakan dalam suatu perjumpaan tatap muka
3. Dibutuhkan orang yang ahli
4. Tujuan diarahkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien.
5. Klien pada akhirnya mampu memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri.
Konseling merupakan suatu proses untuk memebantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangn dirinya,dan untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya ,proses tersebuat dapat terjadi setiap waktu. (Division of Conseling Psychologi)
Menurut Mc Daniel (1956) suatu pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kapadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinyasendiri dan lingkungan.
Konseling meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan,motivasi,dan potensi-potensi yang yang unik dari individu dan membantu individu yang bersangkutan untuk mengapresiasikan ketige hal tersebut. (Berdnard & Fullmer ,1969)
Secara Etimologi berasal dari bahasa Latin “consilium “artinya “dengan” atau bersama” yang dirangkai dengan “menerima atau “memahami” . Sedangkan dalam Bahasa Anglo Saxon istilah konseling berasal dari “sellan” yang berarti ”menyerahkan” atau “menyampaikan”
Menurut Pepinsky dalam Shetzer & Stone (1974), konseling adalah interaksi yang(a)terjadi antara dua orang individu ,masing-masing disebut konselor dan klien ;(b)terjadi dalam suasana yang profesional (c)dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudah kan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien.
Sedangkan, Smith dalam buku yang sama merumuskan bahwa konseling adalah suatu proses dimana konselor membantu konseli membuat interprestasi-interprestasi tetang fakta-fakta yang berhubungan dengn pilihan,rencana,atau penyesuaian-penyesuaian yang perlu dibuat.
Konseling adalah proses pemberian yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien (Prayitno, 1997:106).
Konseling merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada seseorang supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan pada diri sendiri, untuk dimanfaatkan olehnya dan memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang (Mungin Eddy Wibowo, 1986:39).
Dari pengertin tersebut, ciri-ciri pokok konseling, yaitu:
(1) adanya bantuan dari seorang ahli,
(2) proses pemberian bantuan dilakukan dengan wawancara konseling,
(3) bantuan diberikan kepada individu yang mengalami masalah agar memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri dalam mengatasi masalah guna memperbaiki tingkah lakunya di masa yang akan datang.
Dari beberapa pengertian bimbingan dan konseling diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Bimbingan konseling merupakan proses bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan profesional yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing (peserta didik) agar ia dapat berkembang secara optimal, yaitu mampu memahami diri, mengarahkan diri, dan mengaktualisasikan diri, sesuai tahap perkembangan, sifat-sifat, potensi yang dimiliki, dan latar belakang kehidupan serta lingkungannya sehingga tercapai kebahagiaan dalam kehidupannya.
Menurut Tim MKDK IKIP Semarang (1990:5-9) ada lima hal yang melatarbelakangi perlunya layanan bimbingan di sekolah yakni:
(1) masalah perkembangan individu,
(2) masalah perbedaan individual,
(3) masalah kebutuhan individu,
(4) masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku, dan
(5) masalah belajar
2.2 Fungsi Bimbingan Konseling
Sugiyo dkk (1987:14) menyatakan bahwa ada tiga fungsi bimbingan dan konseling, yaitu:
a. Fungsi penyaluran ( distributif )
Fungsi penyaluran ialah fungsi bimbingan dalam membantu menyalurkan siswa-siswa dalam memilih program-program pendidikan yang ada di sekolah, memilih jurusan sekolah, memilih jenis sekolah sambungan ataupun lapangan kerja yang sesuai dengan bakat, minat, cita-cita dan ciri- ciri kepribadiannya. Di samping itu fungsi ini meliputi pula bantuan untuk memiliki kegiatan-kegiatan di sekolah antara lain membantu menempatkan anak dalam kelompok belajar, dan lain-lain.
b. Fungsi penyesuaian ( adjustif ).
Fungsi penyesuaian ialah fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk memperoleh penyesuaian pribadi yang sehat. Dalam berbagai teknik bimbingan khususnya dalam teknik konseling, siswa dibantu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitannya. Fungsi ini juga membantu siswa dalam usaha mengembangkan dirinya secara optimal.
c. Fungsi adaptasi ( adaptif )
Fungsi adaptasi ialah fungsi bimbingan dalam rangka membantu staf sekolah khususnya guru dalam mengadaptasikan program pengajaran dengan ciri khusus dan kebutuhan pribadi siswa-siswa. Dalam fungsi ini pembimbing menyampaikan data tentang ciri-ciri, kebutuhan minat dan kemampuan serta kesulitan-kesulitan siswa kepada guru. Dengan data ini guru berusaha untuk merencanakan pengalaman belajar bagi para siswanya. Sehingga para siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan bakat, cita-cita, kebutuhan dan minat (Sugiyo, 1987:14)
Adapun fungsi khusus bimbingan dan konseling, yakni khususnya di sekolah, menurut H.M. Umar, dkk, dalam Salahudin (2010: 129) adalah sebagai berikut:
Menolong anak dalam kesulitan belajarnya
Berusaha memberikan pelajaran yang sesuai denga minat dan kecakapan anak-anak
Memberi nasihat kepada anak yang akan berhenti dari sekolahnya
Memberi petunjuk kepada anak-anak yang melanjutkan belajarnya, dan sebagainya.
2.3 Prinsip Bimbingan Konseling
Prinsip merupakan paduan hasil kegiatan teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan (Prayitno, 1997:219). Berikut ini prinsip-prinsip bimbingan konseling yang diramu dari sejumlah sumber, sebagai berikut:
a) Sikap dan tingkah laku seseorang sebagai pencerminan dari segala kejiwaannya adakah unik dan khas. Keunikan ini memberikan ciri atau merupakan aspek kepribadian seseorang. Prinsip bimbingan adalah memperhatikan keunikan, sikap dan tingkah laku seseorang, dalam memberikan layanan perlu menggunakan cara-cara yang sesuai atau tepat.
b) Tiap individu mempunyai perbedaan serta mempunyai berbagai kebutuhan. Oleh karenanya dalam memberikan bimbingan agar dapat efektif perlu memilih teknik-teknik yang sesuai dengan perbedaan dan berbagai kebutuhan individu.
c) Bimbingan pada prinsipnya diarahkan pada suatu bantuan yang pada akhirnya orang yang dibantu mampu menghadapi dan mengatasi kesulitannya sendiri.
d) Dalam suatu proses bimbingan orang yang dibimbing harus aktif , mempunyai bayak inisiatif. Sehingga proses bimbingan pada prinsipnya berpusat pada orang yang dibimbing.
e) Prinsip referal atau pelimpahan dalam bimbingan perlu dilakukan. Ini terjadi apabila ternyata masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh sekolah (petugas bimbingan). Untuk menangani masalah tersebut perlu diserahkan kepada petugas atau lembaga lain yang lebih ahli.
f) Pada tahap awal dalam bimbingan pada prinsipnya dimulai dengan kegiatan identifikasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dialami individu yang dibimbing.
g) Proses bimbingan pada prinsipnya dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang dibimbing serta kondisi lingkungan masyarakatnya.
h) Program bimbingan dan konseling di sekolah harus sejalan dengan program pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Hal ini merupakan keharusan karena usaha bimbingan mempunyai peran untuk memperlancar jalannya proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
i) Dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah hendaklah dipimpin oleh seorang petugas yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Di samping itu ia mempunyai kesanggupan bekerja sama dengan petugas-petugas lain yang terlibat.
j) Program bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya senantiasa diadakan penilaian secara teratur. Maksud penilaian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program bimbingan. Prinsip ini sebagai tahap evaluasi dalam layanan bimbingan konseling nampaknya masih sering dilupakan. Padahal sebenarnya tahap evaluasi sangat penting artinya, di samping untuk menilai tingkat keberhasilan juga untuk menyempurnakan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling (Prayitno, 1997:219).
Berdasakan Pedoman Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang Bimbingan Konseling (2004) dinyatakan bahwakerangka kerja layanan BK dikembangkan dalam suatu program BK yang dijabarkan dalam 4 (empat) kegiatan utama, yakni:
a. Layanan dasar bimbingan
Layanan dasar bimbingan adalah bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan ketrampilan-ketrampilan hidup yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan siswa SD.
b. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventik atau mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi layanan responsif adalah:
(1) bidang pendidikan;
(2) bidang belajar;
(3)bidang sosial;
(4) bidang pribadi;
(5) bidang karir;
(6) bidang tata tertib SD;
(7) bidang narkotika dan perjudian;
(8) bidang perilaku sosial, dan
(9)bidang kehidupan lainnya.
c. Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan yang membantu seluruh peserta didik dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir,dan kehidupan sosial dan pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini untuk membantu siswa memantau pertumbuhan dan memahami perkembangan sendiri.
d. Dukungan sistem, adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan memantapkan, memelihara dan meningkatkan progam bimbingan secara menyeluruh. Hal itu dilaksanakan melalui pengembangaan profesionalitas, hubungan masyarakat dan staf, konsultasi dengan guru, staf ahli/penasihat, masyarakat yang lebih luas, manajemen program, penelitian dan pengembangan (Thomas Ellis, 1990)
Kegiatan utama layanan dasar bimbingan yang responsif dan mengandung perencanaan individual serta memiliki dukungan sistem dalam implementasinya didukung oleh beberapa jenis layanan BK, yakni:
(1) layanan pengumpulan data,
(2) layanan informasi,
(3) layanan penempatan,
(4) layanan konseling,
(5) layanan referal/melimpahkan ke pihak lain, dan
(6) layanan penilaian dan tindak lanjut (Nurihsan, 2005:21).
2.4 Peran Guru Bidang Studi dalam Layanan BK
Implementasi kegiatan BK dalam pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi sangat menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu peranan guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan BK sangat penting dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sardiman (2001:142) menyatakan bahwa ada sembilan peran guru dalam kegiatan BK, yaitu:
a) Informator, guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.
b) Organisator, guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran dan lain-lain.
c) Motivator, guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menumbuhkan swadaya (aktivitas) dan daya cipta (kreativitas) sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar-mengajar.
d) Director, guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.
e) Inisiator, guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar-mengajar.
f) Transmitter, guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan.
g) Fasilitator, guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar.
h) Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.
i) Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.
Soetjipto dan Kosasi (2009: 107-111) menyatakan bahwa peranan guru dalam pelaksanaan bimbingan di sekolah dapat dibedakan menjadi dua: (1) tugas dalam layanan bimbingan dalam kelas dan (2) di luar kelas. Dalam layanan bimbingan, guru mempunyai beberapa tugas utama, sebagaimana dituangkan dalam Kurikulum SMA 1975 tentang Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan.
Guru perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang tugas-tugas yang harus dilakukannya dalam kegiatan bimbingan. Kejelasan ini dapat memotivasi guru untuk berperan secara aktif dalam kegiatan bimbingan dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan itu.
Perilaku guru dapat mempengaruhi keberhasilan belajar. Oleh karena itu, guru harus dapat menerapkan fungsi bimbingan dalam kegiatan belajar-mengajar. Sehubungan dengan itu Rochman Natawidjaya dan Moh. Surya dalam Soetjipto dan Kosasi (2009: 108) mengemukakan beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam proses belajar-mengajar sesuai dengan fungsinya sebagai guru dan pembimbing, yaitu:
a) Perlakuan terhadap siswa didasarkan atas keyakinan bahwa sebagai individu, siswa memiliki potensi untuk berkembang dan maju serta mempu mengarahkan dirinya sendiri untuk mandiri.
b) Sikap yang positif dan wajar terhadap siswa.
c) Perlakuan terhadap siswa secara hangat, ramah, rendah hati, menyenanagkan.
d) Pemahaman siswa secara empatik.
e) Penghargaan terhadap martabat siswa sebagai individu.
f) Penampilan diri secara ahli (genuine) tidak berpura-pura di depan siswa.
g) Kekonkretan dalam menyatakan diri.
h) Penerimaan siswa secara apa adanya.
i) Perlakuan terhadap siswa secara permissive.
j) Kepekaan terhadap perasaan yang dinyatakan oleh siswa dan membantu siswa untuk menyadari perasaannya itu.
k) Kesadaran bahwa tujuan mengajar bukan terbatas pada penguasaan siswa terhadap bahan pengajaran saja, melainkan menyangkut pengembangan siswa menjadi individu yang lebih dewasa.
l) Penyesuaian diri terhadap keadaan yang khusus.
Abu Ahmadi (1977) dalam Soetjipto dan Kosasi (2009: 109) mengemukakan peran guru sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar-mengajar, sebagai berikut:
a) Menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap siswa merasa aman, dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapainya mendapat penghargaan dan perhatian.
b) Mengusahakan aagar siswa-siswa dapat memahami dirinya, kecakapan-kecakapan, sikap, minat, dan pembawaannya.
c) Mengembangkan sikap-sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik.
d) Menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
e) Membantu memilih jabatan yang cocok, sesuai dengan bakat, kemampuan, dan minatnya.
Di samping tugas-tugas tersebut, guru juga dapat melakukan tugas-tugas bimbingan dalam proses pembelajaran seperti berikut:
a) Melaksanakan kegiatan diagnostik kesulitan belajar. Dalam hal ini guru mencari atau mengidentifikasi sumber-sumber kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.
b) Guru dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya kepada murid dalam memecahkan masalah pribadi.
Tugas guru dalam layanan bimbingan tidak terbatas dalam kegiatan proses belajar-mengajar atau dalam kelas saja, tetapi juga kegiatan-kegiatan bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas bimbingan itu antara lain:
a) Memberikan pengajaran perbaikan (remedial teaching).
b) Memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa.
c) Melakukan kunjungan rumah (home visit).
d) Menyelenggarakan kelompok belajar, yang bermanfaat untuk: Membiasakan anak untuk bergaul dengan teman-temannya, bagaimana mengemukakan pendapatnya dan menerima pendapat dari teman lain. Merealisasikan tujuan pendidikan dan pengajaran melalui belajar secara kelompok. Mengatasi kesulitan-kesulitan, terutema dalam hal pelajaran secara bersama-sama. Belajar hidup bersama agar nantinya tidak canggungdi dalam masyarakat yang lebih luas. Memupuk rasa kegotongroyongan.
Beberapa contoh kegiatan tersebut memberikan bukti bahwa tugas guru dalam kegiatan bimbingan sangat penting. Kegiatan bimbingan tidak semata-mata tugas konselor saja. Tanpa peran serta guru, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat terwujud secara optimal. Gibson dan Mitchell dalam soetjipto dan kosasi (2009: 111) menyatakan bahwa guru mempunyai peranan yang besar dalam program bimbingan dan konseling di sekolah.
Tugas utama guru kelas dalam layanan BK adalah sebagai berikut:
Membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa.
Melakukan kerja sama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling.
Mengalihtangankan (merujuk) siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing.
Mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling (program perbaikan dan program pengayaan, atau remedial teaching).
Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing
Membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan dan konseling
Menerapkan nilai-nilai bimbingan dalam PBM atau berinteraksi dengan siswa, seperti : bersikap respek kepada semua siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, atau berpendapat, memberikan reward kepada siswa yang menampilkan perilaku/prestasi yang baik, menampilkan pribadi sebagai figur moral yang berfungsi sebagai ”uswah hasanah”.
bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan pada siswa dengan perbandingan 1 : 150 orang
2.5 Evaluasi Guru Bidang Studi dalam Kaitan Bimbingan Konseling
Evaluasi yang dilakukan oleh guru bidang studi kepada para siswa dapat termasuk tugas dalam layanan bimbingan dalam kelas. Guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak.
Shertzer dan Stone (1966) mengemukakan pendapatnya: “Evaluation consist of making systematic judgements of the relative effectiveness with which goals are attained in relation to special standards“.
Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Pengertian lain dari evaluasi ini adalah suatu usaha mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari perkembangan sikap dan perilaku, atau tugas-tugas perkembangan para siswa melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan.
Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu Evaluation. Dalam buku “Essentials of Educational Evaluation”, Edwind Wand dan Gerald W. Brown, mengatakan bahwa : “Evaluation rafer to the act or prosses to determining the value of something”. Jadi menurut Wand dan Brown, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari pada sesuatu. Sesuai dengan pendapat tersebut maka evaluasi pelaksanaan Bimbingan dan Konseling dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah yang diharapkan oleh Departemen Pendidikan.
Sejalan dengan pendapat tersebut, Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi itu merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (evaluand). Sesuatu yang di pertimbangkan itu bisa berupa orang, kegiatan, keadaan atau sesuatu kesatuan tertentu. ( Hamid Hasan 1998).
Dari konsep di atas, ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Pertama, evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari berbagai macam tindakan yang harus dilakukan. Dengan demikian evaluasi bukanlah hasil atau produk, akan tetapi rangkaian kegiatan. Untuk apa tindakan itu dilakukan. Dengan kata lain evaluasi dilakukan untuk menentukan judgment terhadap sesuatu. (Print, 1993).
Kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, berdasarkan hasil pertimbangan evaluasi apakah sesuatu itu mem punyai nilai atau tidak. Dengan kata lain evaluasi dapat menunjukkan kualitas yang dinilai.
Perlu dijelaskan di sini bahwa evaluasi tidak sama artinya dengan pengukuran (measurement). Pengertian pengukuran (measurement) Wand dan Brown mengatakan : “Measurement means the art or prosses of exestaining the extent or quantity of something”. Jadi pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas atau kuantitas dari pada sesuatu. Dari definisi evaluasi atau penilaian dan pengukuran (measurement) yang disebut diatas, maka dapat diketahui perbedaannya dengan jelas antara arti penilaian dan pengukuran. Sehingga pengukuran akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan “How Much”, sedangkan penilaian akan memberikan jawaban dari pertanyaan “What Value”.
Walaupun ada perbedaan antara pengukuran dan penilaian, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Karena antara pengukuran dan penilaian terdapat hubungan yang sangat erat. Penilaian yang tepat terhadap sesuatu terlebih dahulu harus didasarkan atas hasil pengukuran-pengukuran. Pada akhir pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling selalu tercantum suatu kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tertentu.
Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Bagi guru bidang studi evaluasi dapat menentukan evektifitas kinerjanya selama ini; evaluasi sering dianggap sebagai salah satu hal yang menakutkan oleh siswa. Oleh karena itu, memang melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan nasib siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya. Anggapan semacam ini memang harus diluruskan. Evaluasi mestinya dipandang sebagai suatu proses kegiatan pembelajaran. Dengan demikian mestinya evaluasi dijadikan kebutuhan oleh siswa, sebab dengan evaluasi siswa akan tahu tentang keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Ada beberapa fungsi evaluasi yaitu:
1. evaluasi merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Melalui evaluasi siswa akan mendapatkan informasi tentang efektifitas pembelajaran yang dilakukannya. Dari hasil evaluasi siswa akan dapat menentukan bagaimana pembelajaran yang perlu dilakukannya.
2. Evaluasi merupakan alat yang penting untuk mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. Siswa akan tahu bagian mana yang perlu dipelajari lagi dan bagian mana yang tidak perlu.
3. Informasi dari hasil evaluasi dapat digunakan oleh siswa secara individual dalam mengambil keputusan khususnya dalam menentukan masa depan sehubungan dengan pemilihan bidang pekerjaan serta pengembangan karir.
Evaluasi sering dianggap sebagai kegiatan akhir dari suatu proses kegiatan. Demikian diungkapkan Miller (1985). Siswa di evaluasi setelah ia selesai melakukan suatu pelajaran, apakah ia berhasil atau tidak. Evaluasi berhubungan dengan dua fungsi. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven (1967) adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Fungsi sumatif adalah evaluasi itu digunakan untuk melihat keberhasilan suatu program yang direncanakan. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berhubungan dengan pencapaian sesuatu hasil yang dicapai oleh suatu program. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melihat kemajuan belajar siswa. Print (1993) menjelaskan bahwa evaluasi ini dilakukan selama program pembelajaran berlangsung, maka sebenarnya evaluasi ini dapat pula berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Arinya, hasil dari evaluasi formatif dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi guru dalam upaya memperbaiki kinerjanya.
Pendapat “Good” yang dikutip oleh I.Jumhur dan Moch. Surya (1975 :154), tentang evaluasi adalah : “Proses menentukan atau mempertimbangkan nilai atau jumlah sesuatu melalui penilaian yang dilakukan dengan seksama”.Sejalan dengan rumusan di atas, Arthur Jones memberikan batasan tentang evaluasi adalah sebagai berikut : “Proses yang menunjukkan kepada kita sampai berapa jauh tujuan – tujuan program sekolah dapat dilaksanakan”.
Lebih jauh Moch. Surya mengemukakan menilai bimbingan pada hakekatnya mengetahui secara pasti tentang bagaimana organisasi dan administrasi program itu, bagaimana guru-guru dan petugas-petugas bimbingan lainnya dapat berpartisipasi bagaimana pelaksanaan konseling dan bagaimana catatan-catatan kumulatif dapat dikumpulkan. Uraian tersebut merupakan penjabaran dari proses kegiatan Bimbingan dan Konseling, yang akhirnya perlu pula diketahui bagaimana hasil dari pelaksanaan kegiatan itu. Dengan kata lain bahwa penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan Bimbingan dan Konseling ditujukan untuk menilai bagaimana kesesuaian program, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh para petugas Bimbingan, dan bagaimana pula hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan dan Konseling, mengandung tiga aspek penilaian, yaitu:
Penilaian terhadap program Bimbingan dan Konseling.
Penilaian terhadap proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling.
Penilaian terhadap hasil (Product) dari pelaksanaan kegiatan pelayanan Bimbingan dan Konseling.
Seorang guru bidang studi dalam melaksanakan evaluasi terhadap suatu materi yang telah diajarkan dapat pula mengatahui tingkat kematangan dan pengetahuan siswa pada materi itu. Siswa dikatakan berhasil bila evaluasi yang diberikan dapat mencapai standar kompetensi. Sedangkan siswa dikatakan belum berhasil bila hasil dari evaluasi tersebut belum mencapai standar kompetensi yang diberikan. Siswa-siswa yang belum mencapai standar kompetensi inilah yang perlu dipertanyakan dan melalui guru bidang studi inilah jawaban dari permasalahan terhadap suatu materi dapat diselesaikan.
Siswa-siswa yang mengalami masalah dalam proses pembelajaran, guru dapat membantunya dengan melakukan pendekatan, misalnya dengan melakukan pendekatan. Menanyakan apakah materi yang disampaikan terlalu sulit, terlalu banyak, atau memang pada diri siswa tersebut sedang menghadapi suatu masalah dalam kehidupan terlepas dari proses pembelajaran tetapi berdampak pada hasil evaluasi siswa tersebut. Guru bidang studi yang baik perlu memotivasi dan bersifat terbuka serta menerapkan asas kerahasiaan agar siswa tersebut mau terbuka untuk menyampaikan permasalahan. Bila masalah timbul pada proses pembelajaran oleh guru yang dirasa kurang tepat dilaksanakan oleh siswa tersebut, maka seorang guru dapat menerapkan inovasi pada proses kegiatan belajar mengajar agar tidak membosankan, selain itu guru juga dapat meluangkan waktu lebih untuk membimbing siswa yang dirasa kurang memahami materi agar benar-benar paham dan mengerti.
Evaluasi guru bidang studi biologi terhadap siswa dikelas merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran yang dilakukan sebagai proses pengumpulan dan pemanfaatan informasi yang menyeluruh tentang hasil belajar yang diperoleh siswa untuk menetapkan tingkat ketercapaian dan penguasaan kompetensi. Artinya dalam hal ini seorang guru dalam melaksanakan evaluasi melakukan pengumpulan informasi dan dapat mengembangkan berbagai jenis evaluasi, baik evaluasi yang berkaitan dengan pengujian dan pengukuran tingkat kognitif siswa seperti menggunakan tes, maupun evaluasi terhadap perkembangan proses mental melalui penilaian sikap, dan evaluasi terhadap produk atau karya siswa. Evaluasi ini dilakukan dengan penilaian yang secara terus-menerus dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa baik di dalam maupun diluar kelas, seperti laboratorium, dan lain-lain. Dengan demikian kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang tak terpisah dari proses pembelajaran.
Dari uraian di atas, minimal ada 3 manfaat yang ingin dicapai dalam evaluasi yang dilakukan guru bidang studi di dalam kelas:
1. Menjamin agar proses pembelajaran yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencapai kompetensi sesuai dengan rambu-rambu yang terdapat dalam kurikulum.
2. Menentukan berbagai kelemahan dan kelebihan baik yang dilakukan siswa maupun guru selama proses pembelajaran berlangsung. Analisis kelemahan ini sangat berguna untuk perbaikan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisien.
3. Menentukan pencapaian kompetensi oleh siswa, apakah siswa telah mencapai seluruh kompetensi yang diharapkan atau belum; bagian kompetensi mana yang sudah berhasil dikuasai oleh siswa, dan bagian mana yang belum berhasil dikuasai. Kesimpulan semacam ini memang sangat penting untuk diketahui sebagai bahan pelaporan baik kepada siswa itu sendiri, kepada orang tua, maupun kepada pihak yang dianggap perlu dan terkait dengan system penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Sebagai suatu proses, pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh guru bidang studi biologi harus terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi. Dalam kaiatannya dengan pembelajaran, guru bidang studi dapat menyelipkan beberapa prinsip-prinsip dalam bimbingan konseling.
Guru bidang studi dalam penilaian di dalam kelas dapat menyelipkan motivasi peningkatan belajar siswa melalui upaya pemahaman akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Dengan demikian penilaian tidak semata-mata untuk memberikan angka sebagai hasil dari proses pengukuran, akan tetapi siswa perlu memahami makna dari hasil penilaian. Dengan pemahaman ini diharapkan mereka dapat lebih termotivasi dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Adil, yaitu dalam arti setiap siswa memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran tanpa memandang perbedaan social ekonomi, latar belakang budaya dan kemampuan. Oleh karena itulah mereka juga memiliki kesempatan yang sama untuk dievaluasi. Penilaian guru bidang studi menempatkan posisi siswa dalam kesejajaran, dengan demikian setiap siswa akan memperoleh perlakuan yang sama.
Terbuka, artinya alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang dipahami baik oleh penilai maupun yang dinilai. Siswa perlu memahami jenis atau prosedur penilaian yang akan dilakukan beserta criteria penilaian. Keterbukaan ini bukan hanya akan mendorong siswa untuk memperoleh hasil yang baik sehingga motivasi belajar mereka akan bertambah, tetapi sekaligus akan memahami posisi mereka sendiri dalam pencapaian kompetensi.
Penilaian guru bidang studi pada para siswa dilakukan tidak mengenal waktu kapan seharusnya penilaian dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena penilaian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan dan kemajuan siswa dalam pencapaian kompetensi. Dengan demikian, manakala berdasarkan evaluasi seorang siswa diketahui belum mencapai kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka guru bidang studi harus mengulang kembali hingga benar-benar kompetensi itu telah tercapai secara master.
Penilaian yang dilakukan guru bidang studi harus tersusun terarah, sehingga hasilnya benar-benar memberikan makna kepada semua pihak khususnya kepada siswa itu sendiri. Melalui penilaian berbasis kelas, siswa akan mengetahui posisi mereka dalam memperoleh kompetensi. Di samping itu, mereka juga akan memahami kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam mencapai kompetensi. Dengan demikian hasil penilaian itu juga bermakna bagi guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya memperoleh kompetensi (anonim,2003)
DAFTAR PUSTAKA
Depdiknas. 2004. Pedoman Kurikulum Berbasis Kompetensi bidang Bimbingan Konseling. Jakarta: Puskur Balitbang Depdiknas.
Gunawan, Y., dan Catherine, D.L.S. 2001. Pengantara Bimbingan dan Konseling. Jakarta ;PT. Prehallindo
M. Surya. 1988. Pengantar Bimbingan dan Penyuluhan. Jakarta : UT.
Mungin Eddy Wibowo. 1986. Konseling di Sekolah Jilid I. FIP IKIP Semarang.
Nurihsan, Juntika. 2005. Manajemen Bimbingan Konseling di SD Kurikulum 2004. Jakarta: Gramedia Widiasaraan Indonesia.
Oemar Hamalik. 2000. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Prayitno Erman Amti. 1997. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Depdikbud.
Sardiman. 2001. Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soetjipto dan Kosasi, R. 2007. Profesi Keguruan. Jakarta ; Rineka cipta
Sudrajat, A. (2010). Konsep Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. Tersedia: http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/02/03/evaluasi-program-bimbingan-dan-konseling-di-sekolah/
Sudrajat Ahmad. 2008. Peranan Kepala Sekolah, Guru, dan Wali Kelas Dalam
Bimbingan Konseling. http://akhmadsudrajat.wordpress.com/ 2008/08/13/ peranan-kepala-sekolah-guru-dan-wali-kelas-dalam-bimbingan-dan-konseling/ diakses tangal 11 Desember 2011
Sudrajat Ahmad. 2008. Peranan Guru dalam Prose Pendidikan.
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/06/peran-guru-dalam-proses-pendidikan/ diakses tanggal 11 Desember 20201109.
Sugiyo, dkk. 1987. Bimbingan dan Konseling Sekolah. Semarang: FIP IKIP
Semarang.
Sukardi, D.K.1989. Proses Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah.Jakarta; Penerbit Rineka Cipta
Sukardi, D.K.2007. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan konseling di Sekolah.Jakarta; Penerbit Rineka Cipta.
Tim penyusun. 2003. Pengantar Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Tarsito
Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang. 1990. Bimbingan dan Konseling
Sekolah. Semarang: IKIP Semarang Press.