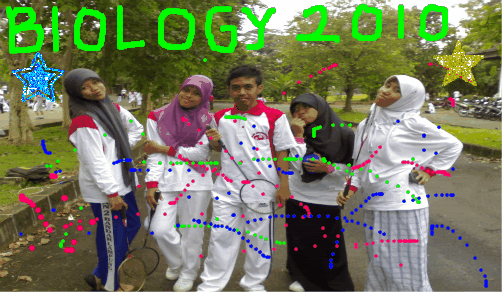A. Pendahuluan
Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Kode Internasional Tatanama Tumbuhan (KITT), nama ilmiah untuk divisi diambil dari kata yang menunjukkan ciri khas yang berlaku untuk seluruh warganya, ditambahkan akhiran –phyta. Schyzophyta memiliki ciri khas yang berkembang biak dengan membelah diri (schizein= membelah, phyton= tumbuhan). Selain itu ada ciri-ciri lain yaitu: tubuhnya uniseluler, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, inti dan plastida belum nyata. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, dan dari segi evolusi termasuk tumbuhan yang paling tua dan paling primitive. Schizophyta dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Bakteri (Bacteria atau Schizomycetes) dan Ganggang biru (ganggang belah= ganggang lendir= Chanophyceae= Schizophyceae= Myxophyceae).
B. Kelas Bacteria/Schizomycetes
Semua anggota bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Uniseluler, dimasukkan dalam golongan jasad renik/mikroba.
• Perkembangan studinya sejalan dengan penemuan mikroskop oleh Antonie Van Leewenhoek (abad 17), dilanjutkan oleh Lousie Pasteur, Davaine, Robert Koch, dan Winogradisky.
• Bentuk bakteri ada 4 macam, yaitu: batang, peluru (bola), koma, dan spiral/spirilum.
• Ukurannya sekitar 0,001 mm; terbesar 100 mikron; terkecil 0,1 mikron.

• Selnya memiliki karakteristik tertentu antara lain:
- Dinding sel berupa peptidoglikan, ada yang dilapisi oleh selaput bergelatin sehingga dalam larutan air menjadi berlendir.
- DNA, RNA tersebar dalam plasma, inti bersifat difus (tersebar) disebut nukleoid.
- Tidak dijumpai plastida, kecuali pada familia Thiorhodaceae yang memiliki derivat klorofil (bakteri ototrof; bakterioklorofil, bakterio viridian, bakterio eritrin) dan karotenoid.
- Pada plasmanya dijumpai vakuola kecil berisi cadangan makanan berupa glikogen, amilose, lemak, protein, dan volutin.

• Bergerak dapat secara aktif atau secara pasif. Bakteri yang bergerak aktif memiliki flagel (= rambut plasma). Macam-macam flagel bakteri, yaitu Monotrikh (1 di ujung), sub polar (2 di bawah rusuk), lofotrikh (banyak di ujung), peritrikh (banyak menyeluruh).

• Pembentukan flagel itu hanya terjadi dalam tingkat tertentudari daur hidupnya, sehingga dalam fase lain dalam hidupnya, bakteri itu tidak mempunyai flagel.
• Bakteri berkembang biak dengan membelah diri setelah itu sel-sel anakan kemudian dapat membentuk koloni (sel bergandengan satu sama lain). Sifat ini dapat menolong identifikasi bakteri. Ada 4 macam koloni bakteri:
a) Diplococcus, koloni terdiri dari sepasang sel berbentuk bola
b) Sarcina, koloni berbentuk kubus
c) Streptococcus, koloni seperti bentuk rantai
d) Staphylococcus, koloni seperti buah anggur

• Cara hidupnya bakteri umumnya adalah heterotrof, sebagai saprofit atau parasit. Namun ada yang autrotrof.
Heterotrof= zat-zat organic yang diperlukan diperoleh dari organism lain
Autotrof= mampu menyediakan sendiri zat-zat organic yang diperlukannya
Saprofit= zat organic diperoleh dari organism yang sudah mati
Parasit= zat organic diperoleh dari organism yang masih hidup
• Sebagai saprofit, bakteri dapat melakukan proses pembusukan bila terjadinya menimbulkan zat-zat berbau busuk dan dinamakan fermentasi bila merupakan suatu pernapasan intramolekuler
• Bakteri parasit ada 3 macam yaitu:
a) Parasit obligat, hidup sebagai parasit saja
b) Parasit fakultatif, dapat hidup sebagai parasit maupun saprofit
c) Patogen, hidup sebagai parasit dan menimbulkan penyakit bagi inangnya.
• Bakteri autotrof dibedakan menjadi 2 golongan
a) Kemoautotrof, bila energi untuk asimilasi (kemosintesis diperoleh dari reaksi kimia, contohnya bakteri nitrit menghasilkan NH3, bakteri nitrat mengoksidasikan HNO2, bakteri belerang mengoksidasikan senyawa belerang.
b) Fotoautotrof, bila energi asimilasi (fotosintesis) diperoleh dari cahaya matahari, contohnya bakteri dari familia Thiorhodaceae.
• Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri digolongkan menjadi:
a) Bakteri aerob, untuk hidupnya memerlukan oksigen bebas.
b) Bakteri anaerob, dapat hidup tanpa oksigen bebas.
• Bakteri dapat hidup dalam bermacam-macam habitat, distribusi luas, kosmopolit di air, tanah, sisa tumbuhan, sisa hewan, daerah tropis, sub tropis.
• Pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya (terlalu panas atau terlalu dingin), bakteri dapat membentuk endospora yaitu badan bulat dengan dinding yang baru berisi zat-zat cadangan makanan.
• Sel-sel bakteri yang membentuk spora tampak sebagai ruangan berisi benda bulat, yang letaknya dapat di salah satu ujung ruang itu, dapat pula di tengah-tengah.

• Peranan bakteri bagi manusia ada yang menguntungkan ada juga yang merugikan.
a) Menguntungkan:
- mengubah nira menjadi tuak (Saccharomyces tuac)
- mengubah alkohol menjadi gula (Mycoderma aceti)
- mengubah susu menjadi yoghurt (Lactobacillus caucasicus)
- bersimbiosis membentuk bintil akar, memfiksasi N2 bebas menjadi pupuk (Rhiobium leguminosarium)
- mengubah protein menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman (Nitrosomonas javanensis, Nitrobacter agilis)
b) merugikan:
- membusukkan bahan makanan, dapat diatasi dengan pengeringan, penambahan gula/garam, pengasaman, pendinginan, pasteurisasi.
- Menimbulkan penyakit pada tumbuhan, hewan, manusia. Pseudomonas solanacearum (menyerang Solanaceae), Bacillus anthracis (menyebabkan penyakit antraks), Vibrio cholera (penyakit kolera), Mycobacterium tuberculosis (TBC).
• Klasifikasi dari kelas bakteri amat sulit, yang ada belum memuaskan. Kurangnya diferensiasi morfologi merupakan salah satu sebabnya. Sehingga cara penggolongan kadang hanya berdasarkan sifat fisiologinya saja.
• Salah satu klasifikasi bakteri yang banyak dipakai dalam taksonomi, menyatakan bahwa kelas Bacteria dibagi dalam 7 bangsa/ordo, yaitu:
1) Pseudomonadales
2) Chlamydobacteriales
3) Eubacteriales
4) Actinomycetales
5) Beggiatoales
6) Myxobacteriales
7) Spirochaetales
Masing-masing bangsa tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Bangsa Pseudomonadales
• Bentuk sel peluru, batang lurus, bengkok, spiral, rantai.
• Selnya sering mengandung pigmen fotosintetik berwana hijau atau lembayung.
• Bergerak dengan flagel yang polar.
• Terdiri dari 6 suku/familia yaitu:
a) Thiorhodaceae
- Plastida berwarna lembayung, disebut bakteri lembayung, dapat berfotosintesis
- Dalam lingkungan dengan H2S, ada tetes belerang dalam selnya.
- Contoh: Thiosarcina rosea, Thiocapsa floridana, Thiodictyon elegans, Thiospirillum sanguineum.

b) Nitrobacteriaceae
- Bakteri kemoautotrof dan memperoleh energi untuk asimilasi dari oksidasi metan, disebut bakteri nitrat.
- Contoh: Nitrosomonas europea, Nitrosococcus nitrosus, Nitrobacter winogradiskyi, Nitrobacter agile.

c) Methanomonadaceae
- Bakteri kemoautotrof dan memperoleh energi untuk asimilasi dari oksida metan, hydrogen, karbon monoksida, disebut bakteri metan.
- Contohnya Methylomonas methanica, Hydrogenomonas flava, Carboxydomonas obligocarbophila.

d) Thiobacteriaceae
- Disebut bakteri belerang, kemoautotrof, dan memperoleh energi dengan oksidasi senyawa-senyawa belerang.
- Dalam plasmanya, belerang bebas ada dalam bentuk butir-butir atau Kristal.
- Contoh: Thiobacillus thioparus, Thiobacterium cristalliferum, Thiospora bipanctata.

e) Pseudomonadaceae
- Bakteri heterotrof, jarang autotrof fakultatif.
- Sel-selnya seringkali bersifat oksidatif, kadang-kadang fermentative.
- Contoh Pseudomonas cocovernanans (racun tempe bongkrek), Pseudomonas solanacearum (menimbulkan penyakit layu pada Solanaceae dan kacang tanah), Pseudomonas denitrificans (mereduksi nitrat menjadi N2).

f) Spirillaceae
- Bakteri-bakteri dengan tubuh yang bengkok, berbentuk koma sampai spiral.
- Contoh: Vibrio coma (Vibrio cholera), penyebab penyakit muntaber; Desulfovibrio desulfuricans, mereduksi sulfat menjadi sulfide; Spirillum minus; Spirillum lipoferum.

2. Bangsa Chlamydobacteriales
• Bentuk sel seperti benang, kadang diselubungi sarungsarung yang mengandung senyawa besi.
• Sel yang terlepas dari koloninya dapat bergerak bebas.
• Bangsa ini dibedakan menjadi 2 suku, yaitu:
a) Chlamidobacteriaceae
- Koloni berbentuk benang, kadang dengan cabang semu.
- Dapat membentuk sel kembara yang bergerak aktif.
- Bakteri besi dengan sarung koloni mengandung senyawa besi.
- Contoh: Sphaerotilus natans, S. dichotomus, Leptothrix ochracea.
b) Crenotrichaceae
- Koloni berbentuk benang, tidak menghasilkan sel-sel kembara.
- Contoh: Crenotrix polyspora.

3. Bangsa Eubacteriales
• Bentuk sel bulat, batang lurus, terpisah atau berantai.
• Bergerak dengan flagel peritrikh, tapi ada juga yang tidak bergerak.
• Terdiri dari 7 bangsa/ordo yaitu:
a) Azotobacteriaceae
- Sel-sel jorong atau batang, mirip sel khamir.
- Hidup bebas dalam tanah, penambat N2.
- Contoh: Azotobacter chorococcum, A. indicus, A. agilis.

b) Rizobacteriaceae
- Sel-sel bentuk batang, kadang bercabang.
- Seringkali bersimbiosis dengan tumbuhan Leguminosae membentuk bintil akar.
- Contoh: Rhizobium leguminosarum (membentuk bintil pada Lathyrus, Pisum, Vicia), R. japonicum (pada kedelai), R. phaseoli (pada Phaseolus).

c) Enterobacteriaceae
- Menimbulkan fermentasi anaerobic pada glukosa, kadang laktosa.
- Sering terdapat pada saluran pernapasan dan saluran kencing vertebrata.
- Lainnya hidup bebas dan bersifat patogen.
- Contoh: Eschericia coli, Salmonella thyposa, S. parathypi, Shigella dysentriae.

d) Micrococcaceae
- Bentuk sel seperti peluru, atau dalam bentuk koloni tetrad, kubus, atau massa tak beraturan.
- Contoh: Sarcina lutea, S. aurantiaca, Micrococcus denitrificans, Staphylococcus aureus.

e) Neisseriaceae
- Sel-sel berbentuk peluru, seringkali berpasangan.
- Contoh: Neisseria gonorrhoeae (Micrococcus gonorrhoeae) penyebab penyakit kencing nanah, N. meningitides (penyebab meningitis).

f) Lactobacillaceae
- Bakteri bentuk peluru atau batang, menimbulkan fermentasi asam laktat.
- Disebut bakteri laktat.
- Contoh: Lactobacillus caucasicus (yoghurt), Streptococcus pygenes (menimbulkan nanah atau keracunan darah), Diplococcus pneumonia (pneumonia).
g) Bacillaceae
- Sel-sel bentuk batang, menghasilkan endospora.
- Contoh: Bacillus subtilis (penghasil basitrasin), B. atracis (penyakit antraks), B. polymixa (penghasil polimiksin), Clostridium pasteurianum (penambat N2).



4. Bangsa Actinomycetales
• Sel bentuk batang memanjang mirip hifa jamur, dan cenderung bercabang-cabang.
• Anggotanya terdiri berbagai jenis jamur yang bersuku sebagai berikut:
a) Mycobacteriaceae
- Sel-sel tidak membentuk miselium atau hanya miselium yang rudimenter.
- Contoh: Mycobacterium tuberculosis (penyebab TBC), M. leprae (lepra/kusta).

b) Actinomycetaceae
- Membentuk miselium, spora terbentuk dalam fragmen-fragmen miselium.
- Contoh: Actinomyces bovis (penyebab penyakit mulut pada ternak).

c) Streptomycetaceae
- Membentuk miselium, miselium vegetatif tidak terbagi-bagi.
- Contoh: Streptomyces aurefaciens (menghasilkan aureomisin); S. griseus (streptomisin); S. fradiae (neomisin dan fradisin); S. rimosus (tetramisin)

5. Bangsa Beggiatoales
• Sel bentuk kokus atau berbentuk benang dengan butir belerang, baik di dalam atau di permukaan tubuh.
• Bergerak dengan meluncur, berkelok atau berguling, dan tidak berflagel.
• Terdiri dari satu suku yaitu suku Beggiatoaceae, dengan ciri-ciri:
- Sel-sel berbentuk benang dengan butir belerang di dalam atau dipermkaan sel.
- Dalam lingkungan kaya H2S di selnya sering terdapat butir-butir belerang.
- Contoh: Beggiatoa alba, B. gigantean, Thiospirillopsis floridana (dalam sumber air belerang), Thotrix nivea (dalam air tawar mengandung H2S).

6. Bangsa Mycobacteriales
• Sel-selnya berbentuk batang yang lentur, merayap pada subtrat yang padat membentuk koloni yang tipis merata pada subtrat (lendir).
• Dapat membentuk tubuh buah.
• Terdiri dari bakteri-bakteri lendir yang terbagi menjadi 2 famili yaitu:
a) Cytophagaceae
- Tidak membentuk tubuh buah maupun sel-sel istirahat (mikrokista).
- Dapat membentuk zat warna tertentu.
- Contoh: Cyptohaga lutea (membentuk zat warna kuning), C. ruba (merah jambu).

b) Myxococcae
- Mikrosista bulat atau jorong, punya dinding nyata.
- Contoh: Sporocytophaga myxoccoides: sel spiral, lentur, bergerak seperti ular; Myxococcus virescens, dengan tubuh buah berwarna kuning kehijauan.

7. Bangsa Spirochaetales
• Sel-sel langsing, lentur, panjang berukuran 6-500 µm.
• Terdiri dari 2 suku yaitu:
a) Spirochaetaceae
- Sel berukuran 30-500 mikron, mempunyai struktur protoplasma tertentu
- Anggotanya penghuni air tawar yang menggenang atau air laut atau hidup dalam alat pencernaan makanan kerang.
- Contoh: Spirochaeta plicatilis (dalam air tawar atau air laut), Cristispira balbianii (parasit pada ikan).
b) Treponemataceae
- Berbentuk spiral, panjang tubuh 4-16 mikron.
- Contoh: Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis; T. pertenue, penyakit frambusia; Borelia anseria, patogen untuk burung.

C. Kelas Cyanophyceae
Disebut alga biru atau ganggang belah (Schizophyceae) atau ganggang lendir (Myxophyceae), yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Uniseluler, atau berkoloni berbentuk benang dengan struktur yang masih sederhana.
• Berkembang biak dengan membelah tubuhnya.
• Memiliki cadangan makanan berupa glikogen/butir-butir sianofisin (lipoprotein) diperifer, serta ada juga yang berupa volutin.
• Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang bila bereaksi dengan air seperti lendir.
• Pada plasma bagian tepi terdapat klorofil a, karotenoid, fikosianin, fikoklorofil, yang belum terlokalisasi dan sifatnya labil menyebabkan warna tidak tetap. Sifat ini disebut adaptasi kromatik (yaitu jika cahaya hijau mengenai ganggang ini akan berwarna merah, sedang cahaya merah mengenai ganggang ini akan berwarna hijau/biru). Kromatofora ini sangat berkaitan erat dengan fotosintesis I.
• Inti sel bersifat difus, di tengah sel, belum jelas hanya terdapat DNA/RNA belum terlokalisasi dan kromosom belum jelas tampak.
• Pada sel yang tua terdapat vakuola.
• Umumnya tidak bergerak, namun dari jenis-jenis yang berbentuk benang dapat mengadakan gerakan meluncur sambil mengeluarkan lendir.

• Chanophyceae dibagi menjadi 3 bangsa/ordo yaitu:
1) Chorococcales
2) Chamaesiphonales
3) Hormogonales
Adapun deskripsi mengenai ke 3 bangsa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bangsa Chorococcales
• Bentuk sel membulat tunggal atau berkelompok.
• Memiliki klorofil, karotenoid, fikosianin, fikoklorofil.
• Berwarna kehijauan pada habitat berair.
• Di bagian tepi protoplasma/dinding sel berlendir (menyebabkan warna berkilau).
• Menyenangi tempat lembab seperti batu cadas dan tembok.
• Anggota ordo ini yaitu: Familia Chorococcae
• Contoh: Chorococcus turgidus, Gleocapsa sanguine.

2. Bangsa Chamaesiphonales
• Bentuk sel bulat tunggal atau berkoloni bentuk benang.
• Koloni dapat putus jika akan membentuk horomogonium (= sel yang tidak terisi protoplas, selnya jernih dengan dinding sel yang jelas).
• Potongan koloni dapat bergerak merayap dan membentuk koloni baru.
• Dapat juga membentuk endospora dan keluar dari sel tumbuh menjadi individu baru.
• Anggota ordo ini yaitu: Familia Chamaesiphonaceae
• Contoh: Chamaesiphon confervicolus.

3. Bangsa Hormogonales
• Bentuk sel bulat dengan sudut membulat dan persegi
• Koloni berbentuk benang.
• Benang bercabang palsu terbentuk dari keluarnya plasma dari dinding sel dan terbentuklah hormogonium.
• Anggota ordo ini adalah:
a) Familia Oscilatoriaceae
- Hidup dalam air atau di atas tanah basah.
- Bentuk sel bulat dengan sudut persegi.
- Dapat membentuk koloni benang, dan dinding sel mengeluarkan lendir.
- Pada jarak tertentu pada benang terdapat sel-sel yang dindingnya tebal, berwarna kekuningan (hilang kromatofornya), disebut heterosista. Heterosista dapat tumbuh menjadi benang yang baru, fungsinya belum jelas, biasanya lekas mati.
- Contoh: Oscillatoria linosa, O. princeps.

b) Familia Rivulariaceae
- Membentuk percabangan yang banyak.
- Pangkalnya terdiri atas suatu heterosista, ujungnya berambut.
- Contoh: Rivularia bullata, R. haematites.

c) Familia Nostotaceae
- Sel bulat memenjang dengan ujung membulat, terbentuk heterosista dan akinet (sel berisi klorofil) di sebagian besar selnya.
- Dapat menambat N dari udara, seringkali bersimbiosis dengan Fungi dan Lichenes.
- Contoh: Nostoc commune, N. sphaeroides, Anabaena cycaeae ( bersimbiosis dengan pakis haji/Cycas rumphii dalam akar-akarnya yang berbentuk seperti bunga karang), A. azollae (bersimbiosis dengan Azolla pinnata sejenis paku air, dalam daunnya yang hidup di sawah atau di rawa).

Daftar Pustaka
Brock, T.D. dan M.T. Madigan. 1991. Biology of Microorganisma. Prentice Hall, Inc. USA.
Kimball, J.W. 1992. Biologi. Jilid 3. Erlangga. Jakarta.
Scheeler, P. dan D.E. Bianchi. 1987. Cell and Molecular Biology. John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
Smith, G.M. 1965. Cryptogamic Botany (Schizophyta and Thallophyta). Mc Graw-Hill, Inc. New York.
Tjirosoepomo, G. 1998. Taksonomi Tumbuhan: Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
sumber: Hasnunidah, Neni. 2007. Botani Tumbuhan Rendah. Unila. Bandarlampung.
Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Kode Internasional Tatanama Tumbuhan (KITT), nama ilmiah untuk divisi diambil dari kata yang menunjukkan ciri khas yang berlaku untuk seluruh warganya, ditambahkan akhiran –phyta. Schyzophyta memiliki ciri khas yang berkembang biak dengan membelah diri (schizein= membelah, phyton= tumbuhan). Selain itu ada ciri-ciri lain yaitu: tubuhnya uniseluler, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas, inti dan plastida belum nyata. Tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, dan dari segi evolusi termasuk tumbuhan yang paling tua dan paling primitive. Schizophyta dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu Bakteri (Bacteria atau Schizomycetes) dan Ganggang biru (ganggang belah= ganggang lendir= Chanophyceae= Schizophyceae= Myxophyceae).
B. Kelas Bacteria/Schizomycetes
Semua anggota bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Uniseluler, dimasukkan dalam golongan jasad renik/mikroba.
• Perkembangan studinya sejalan dengan penemuan mikroskop oleh Antonie Van Leewenhoek (abad 17), dilanjutkan oleh Lousie Pasteur, Davaine, Robert Koch, dan Winogradisky.
• Bentuk bakteri ada 4 macam, yaitu: batang, peluru (bola), koma, dan spiral/spirilum.
• Ukurannya sekitar 0,001 mm; terbesar 100 mikron; terkecil 0,1 mikron.

• Selnya memiliki karakteristik tertentu antara lain:
- Dinding sel berupa peptidoglikan, ada yang dilapisi oleh selaput bergelatin sehingga dalam larutan air menjadi berlendir.
- DNA, RNA tersebar dalam plasma, inti bersifat difus (tersebar) disebut nukleoid.
- Tidak dijumpai plastida, kecuali pada familia Thiorhodaceae yang memiliki derivat klorofil (bakteri ototrof; bakterioklorofil, bakterio viridian, bakterio eritrin) dan karotenoid.
- Pada plasmanya dijumpai vakuola kecil berisi cadangan makanan berupa glikogen, amilose, lemak, protein, dan volutin.

• Bergerak dapat secara aktif atau secara pasif. Bakteri yang bergerak aktif memiliki flagel (= rambut plasma). Macam-macam flagel bakteri, yaitu Monotrikh (1 di ujung), sub polar (2 di bawah rusuk), lofotrikh (banyak di ujung), peritrikh (banyak menyeluruh).

• Pembentukan flagel itu hanya terjadi dalam tingkat tertentudari daur hidupnya, sehingga dalam fase lain dalam hidupnya, bakteri itu tidak mempunyai flagel.
• Bakteri berkembang biak dengan membelah diri setelah itu sel-sel anakan kemudian dapat membentuk koloni (sel bergandengan satu sama lain). Sifat ini dapat menolong identifikasi bakteri. Ada 4 macam koloni bakteri:
a) Diplococcus, koloni terdiri dari sepasang sel berbentuk bola
b) Sarcina, koloni berbentuk kubus
c) Streptococcus, koloni seperti bentuk rantai
d) Staphylococcus, koloni seperti buah anggur

• Cara hidupnya bakteri umumnya adalah heterotrof, sebagai saprofit atau parasit. Namun ada yang autrotrof.
Heterotrof= zat-zat organic yang diperlukan diperoleh dari organism lain
Autotrof= mampu menyediakan sendiri zat-zat organic yang diperlukannya
Saprofit= zat organic diperoleh dari organism yang sudah mati
Parasit= zat organic diperoleh dari organism yang masih hidup
• Sebagai saprofit, bakteri dapat melakukan proses pembusukan bila terjadinya menimbulkan zat-zat berbau busuk dan dinamakan fermentasi bila merupakan suatu pernapasan intramolekuler
• Bakteri parasit ada 3 macam yaitu:
a) Parasit obligat, hidup sebagai parasit saja
b) Parasit fakultatif, dapat hidup sebagai parasit maupun saprofit
c) Patogen, hidup sebagai parasit dan menimbulkan penyakit bagi inangnya.
• Bakteri autotrof dibedakan menjadi 2 golongan
a) Kemoautotrof, bila energi untuk asimilasi (kemosintesis diperoleh dari reaksi kimia, contohnya bakteri nitrit menghasilkan NH3, bakteri nitrat mengoksidasikan HNO2, bakteri belerang mengoksidasikan senyawa belerang.
b) Fotoautotrof, bila energi asimilasi (fotosintesis) diperoleh dari cahaya matahari, contohnya bakteri dari familia Thiorhodaceae.
• Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri digolongkan menjadi:
a) Bakteri aerob, untuk hidupnya memerlukan oksigen bebas.
b) Bakteri anaerob, dapat hidup tanpa oksigen bebas.
• Bakteri dapat hidup dalam bermacam-macam habitat, distribusi luas, kosmopolit di air, tanah, sisa tumbuhan, sisa hewan, daerah tropis, sub tropis.
• Pada kondisi yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya (terlalu panas atau terlalu dingin), bakteri dapat membentuk endospora yaitu badan bulat dengan dinding yang baru berisi zat-zat cadangan makanan.
• Sel-sel bakteri yang membentuk spora tampak sebagai ruangan berisi benda bulat, yang letaknya dapat di salah satu ujung ruang itu, dapat pula di tengah-tengah.

• Peranan bakteri bagi manusia ada yang menguntungkan ada juga yang merugikan.
a) Menguntungkan:
- mengubah nira menjadi tuak (Saccharomyces tuac)
- mengubah alkohol menjadi gula (Mycoderma aceti)
- mengubah susu menjadi yoghurt (Lactobacillus caucasicus)
- bersimbiosis membentuk bintil akar, memfiksasi N2 bebas menjadi pupuk (Rhiobium leguminosarium)
- mengubah protein menjadi senyawa yang dapat diserap tanaman (Nitrosomonas javanensis, Nitrobacter agilis)
b) merugikan:
- membusukkan bahan makanan, dapat diatasi dengan pengeringan, penambahan gula/garam, pengasaman, pendinginan, pasteurisasi.
- Menimbulkan penyakit pada tumbuhan, hewan, manusia. Pseudomonas solanacearum (menyerang Solanaceae), Bacillus anthracis (menyebabkan penyakit antraks), Vibrio cholera (penyakit kolera), Mycobacterium tuberculosis (TBC).
• Klasifikasi dari kelas bakteri amat sulit, yang ada belum memuaskan. Kurangnya diferensiasi morfologi merupakan salah satu sebabnya. Sehingga cara penggolongan kadang hanya berdasarkan sifat fisiologinya saja.
• Salah satu klasifikasi bakteri yang banyak dipakai dalam taksonomi, menyatakan bahwa kelas Bacteria dibagi dalam 7 bangsa/ordo, yaitu:
1) Pseudomonadales
2) Chlamydobacteriales
3) Eubacteriales
4) Actinomycetales
5) Beggiatoales
6) Myxobacteriales
7) Spirochaetales
Masing-masing bangsa tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Bangsa Pseudomonadales
• Bentuk sel peluru, batang lurus, bengkok, spiral, rantai.
• Selnya sering mengandung pigmen fotosintetik berwana hijau atau lembayung.
• Bergerak dengan flagel yang polar.
• Terdiri dari 6 suku/familia yaitu:
a) Thiorhodaceae
- Plastida berwarna lembayung, disebut bakteri lembayung, dapat berfotosintesis
- Dalam lingkungan dengan H2S, ada tetes belerang dalam selnya.
- Contoh: Thiosarcina rosea, Thiocapsa floridana, Thiodictyon elegans, Thiospirillum sanguineum.

b) Nitrobacteriaceae
- Bakteri kemoautotrof dan memperoleh energi untuk asimilasi dari oksidasi metan, disebut bakteri nitrat.
- Contoh: Nitrosomonas europea, Nitrosococcus nitrosus, Nitrobacter winogradiskyi, Nitrobacter agile.

c) Methanomonadaceae
- Bakteri kemoautotrof dan memperoleh energi untuk asimilasi dari oksida metan, hydrogen, karbon monoksida, disebut bakteri metan.
- Contohnya Methylomonas methanica, Hydrogenomonas flava, Carboxydomonas obligocarbophila.

gambar: bakteri metan: (kiri) Methylomonas methanica, berdiameter 0,6 mikron. (kanan) Methilococcus capsulatus, berdiameter 1 mikron (dikutip dari Brock and Madigan,1991)
d) Thiobacteriaceae
- Disebut bakteri belerang, kemoautotrof, dan memperoleh energi dengan oksidasi senyawa-senyawa belerang.
- Dalam plasmanya, belerang bebas ada dalam bentuk butir-butir atau Kristal.
- Contoh: Thiobacillus thioparus, Thiobacterium cristalliferum, Thiospora bipanctata.

gambar: bakteri belerang Thiobacillus neapolitamus berdiameter 1 mikron (dikutip dari Brock and Madigan,1991)
e) Pseudomonadaceae
- Bakteri heterotrof, jarang autotrof fakultatif.
- Sel-selnya seringkali bersifat oksidatif, kadang-kadang fermentative.
- Contoh Pseudomonas cocovernanans (racun tempe bongkrek), Pseudomonas solanacearum (menimbulkan penyakit layu pada Solanaceae dan kacang tanah), Pseudomonas denitrificans (mereduksi nitrat menjadi N2).

gambar: bakteri Pseudomonas cepacia pada mdia agar (dikutip dari Brock and Madigan,1991)
f) Spirillaceae
- Bakteri-bakteri dengan tubuh yang bengkok, berbentuk koma sampai spiral.
- Contoh: Vibrio coma (Vibrio cholera), penyebab penyakit muntaber; Desulfovibrio desulfuricans, mereduksi sulfat menjadi sulfide; Spirillum minus; Spirillum lipoferum.

2. Bangsa Chlamydobacteriales
• Bentuk sel seperti benang, kadang diselubungi sarungsarung yang mengandung senyawa besi.
• Sel yang terlepas dari koloninya dapat bergerak bebas.
• Bangsa ini dibedakan menjadi 2 suku, yaitu:
a) Chlamidobacteriaceae
- Koloni berbentuk benang, kadang dengan cabang semu.
- Dapat membentuk sel kembara yang bergerak aktif.
- Bakteri besi dengan sarung koloni mengandung senyawa besi.
- Contoh: Sphaerotilus natans, S. dichotomus, Leptothrix ochracea.
b) Crenotrichaceae
- Koloni berbentuk benang, tidak menghasilkan sel-sel kembara.
- Contoh: Crenotrix polyspora.

3. Bangsa Eubacteriales
• Bentuk sel bulat, batang lurus, terpisah atau berantai.
• Bergerak dengan flagel peritrikh, tapi ada juga yang tidak bergerak.
• Terdiri dari 7 bangsa/ordo yaitu:
a) Azotobacteriaceae
- Sel-sel jorong atau batang, mirip sel khamir.
- Hidup bebas dalam tanah, penambat N2.
- Contoh: Azotobacter chorococcum, A. indicus, A. agilis.

b) Rizobacteriaceae
- Sel-sel bentuk batang, kadang bercabang.
- Seringkali bersimbiosis dengan tumbuhan Leguminosae membentuk bintil akar.
- Contoh: Rhizobium leguminosarum (membentuk bintil pada Lathyrus, Pisum, Vicia), R. japonicum (pada kedelai), R. phaseoli (pada Phaseolus).

c) Enterobacteriaceae
- Menimbulkan fermentasi anaerobic pada glukosa, kadang laktosa.
- Sering terdapat pada saluran pernapasan dan saluran kencing vertebrata.
- Lainnya hidup bebas dan bersifat patogen.
- Contoh: Eschericia coli, Salmonella thyposa, S. parathypi, Shigella dysentriae.

d) Micrococcaceae
- Bentuk sel seperti peluru, atau dalam bentuk koloni tetrad, kubus, atau massa tak beraturan.
- Contoh: Sarcina lutea, S. aurantiaca, Micrococcus denitrificans, Staphylococcus aureus.

e) Neisseriaceae
- Sel-sel berbentuk peluru, seringkali berpasangan.
- Contoh: Neisseria gonorrhoeae (Micrococcus gonorrhoeae) penyebab penyakit kencing nanah, N. meningitides (penyebab meningitis).

f) Lactobacillaceae
- Bakteri bentuk peluru atau batang, menimbulkan fermentasi asam laktat.
- Disebut bakteri laktat.
- Contoh: Lactobacillus caucasicus (yoghurt), Streptococcus pygenes (menimbulkan nanah atau keracunan darah), Diplococcus pneumonia (pneumonia).
g) Bacillaceae
- Sel-sel bentuk batang, menghasilkan endospora.
- Contoh: Bacillus subtilis (penghasil basitrasin), B. atracis (penyakit antraks), B. polymixa (penghasil polimiksin), Clostridium pasteurianum (penambat N2).



4. Bangsa Actinomycetales
• Sel bentuk batang memanjang mirip hifa jamur, dan cenderung bercabang-cabang.
• Anggotanya terdiri berbagai jenis jamur yang bersuku sebagai berikut:
a) Mycobacteriaceae
- Sel-sel tidak membentuk miselium atau hanya miselium yang rudimenter.
- Contoh: Mycobacterium tuberculosis (penyebab TBC), M. leprae (lepra/kusta).

b) Actinomycetaceae
- Membentuk miselium, spora terbentuk dalam fragmen-fragmen miselium.
- Contoh: Actinomyces bovis (penyebab penyakit mulut pada ternak).

c) Streptomycetaceae
- Membentuk miselium, miselium vegetatif tidak terbagi-bagi.
- Contoh: Streptomyces aurefaciens (menghasilkan aureomisin); S. griseus (streptomisin); S. fradiae (neomisin dan fradisin); S. rimosus (tetramisin)

5. Bangsa Beggiatoales
• Sel bentuk kokus atau berbentuk benang dengan butir belerang, baik di dalam atau di permukaan tubuh.
• Bergerak dengan meluncur, berkelok atau berguling, dan tidak berflagel.
• Terdiri dari satu suku yaitu suku Beggiatoaceae, dengan ciri-ciri:
- Sel-sel berbentuk benang dengan butir belerang di dalam atau dipermkaan sel.
- Dalam lingkungan kaya H2S di selnya sering terdapat butir-butir belerang.
- Contoh: Beggiatoa alba, B. gigantean, Thiospirillopsis floridana (dalam sumber air belerang), Thotrix nivea (dalam air tawar mengandung H2S).

6. Bangsa Mycobacteriales
• Sel-selnya berbentuk batang yang lentur, merayap pada subtrat yang padat membentuk koloni yang tipis merata pada subtrat (lendir).
• Dapat membentuk tubuh buah.
• Terdiri dari bakteri-bakteri lendir yang terbagi menjadi 2 famili yaitu:
a) Cytophagaceae
- Tidak membentuk tubuh buah maupun sel-sel istirahat (mikrokista).
- Dapat membentuk zat warna tertentu.
- Contoh: Cyptohaga lutea (membentuk zat warna kuning), C. ruba (merah jambu).

b) Myxococcae
- Mikrosista bulat atau jorong, punya dinding nyata.
- Contoh: Sporocytophaga myxoccoides: sel spiral, lentur, bergerak seperti ular; Myxococcus virescens, dengan tubuh buah berwarna kuning kehijauan.

7. Bangsa Spirochaetales
• Sel-sel langsing, lentur, panjang berukuran 6-500 µm.
• Terdiri dari 2 suku yaitu:
a) Spirochaetaceae
- Sel berukuran 30-500 mikron, mempunyai struktur protoplasma tertentu
- Anggotanya penghuni air tawar yang menggenang atau air laut atau hidup dalam alat pencernaan makanan kerang.
- Contoh: Spirochaeta plicatilis (dalam air tawar atau air laut), Cristispira balbianii (parasit pada ikan).
b) Treponemataceae
- Berbentuk spiral, panjang tubuh 4-16 mikron.
- Contoh: Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis; T. pertenue, penyakit frambusia; Borelia anseria, patogen untuk burung.

C. Kelas Cyanophyceae
Disebut alga biru atau ganggang belah (Schizophyceae) atau ganggang lendir (Myxophyceae), yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
• Uniseluler, atau berkoloni berbentuk benang dengan struktur yang masih sederhana.
• Berkembang biak dengan membelah tubuhnya.
• Memiliki cadangan makanan berupa glikogen/butir-butir sianofisin (lipoprotein) diperifer, serta ada juga yang berupa volutin.
• Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa yang bila bereaksi dengan air seperti lendir.
• Pada plasma bagian tepi terdapat klorofil a, karotenoid, fikosianin, fikoklorofil, yang belum terlokalisasi dan sifatnya labil menyebabkan warna tidak tetap. Sifat ini disebut adaptasi kromatik (yaitu jika cahaya hijau mengenai ganggang ini akan berwarna merah, sedang cahaya merah mengenai ganggang ini akan berwarna hijau/biru). Kromatofora ini sangat berkaitan erat dengan fotosintesis I.
• Inti sel bersifat difus, di tengah sel, belum jelas hanya terdapat DNA/RNA belum terlokalisasi dan kromosom belum jelas tampak.
• Pada sel yang tua terdapat vakuola.
• Umumnya tidak bergerak, namun dari jenis-jenis yang berbentuk benang dapat mengadakan gerakan meluncur sambil mengeluarkan lendir.

• Chanophyceae dibagi menjadi 3 bangsa/ordo yaitu:
1) Chorococcales
2) Chamaesiphonales
3) Hormogonales
Adapun deskripsi mengenai ke 3 bangsa tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bangsa Chorococcales
• Bentuk sel membulat tunggal atau berkelompok.
• Memiliki klorofil, karotenoid, fikosianin, fikoklorofil.
• Berwarna kehijauan pada habitat berair.
• Di bagian tepi protoplasma/dinding sel berlendir (menyebabkan warna berkilau).
• Menyenangi tempat lembab seperti batu cadas dan tembok.
• Anggota ordo ini yaitu: Familia Chorococcae
• Contoh: Chorococcus turgidus, Gleocapsa sanguine.

2. Bangsa Chamaesiphonales
• Bentuk sel bulat tunggal atau berkoloni bentuk benang.
• Koloni dapat putus jika akan membentuk horomogonium (= sel yang tidak terisi protoplas, selnya jernih dengan dinding sel yang jelas).
• Potongan koloni dapat bergerak merayap dan membentuk koloni baru.
• Dapat juga membentuk endospora dan keluar dari sel tumbuh menjadi individu baru.
• Anggota ordo ini yaitu: Familia Chamaesiphonaceae
• Contoh: Chamaesiphon confervicolus.

3. Bangsa Hormogonales
• Bentuk sel bulat dengan sudut membulat dan persegi
• Koloni berbentuk benang.
• Benang bercabang palsu terbentuk dari keluarnya plasma dari dinding sel dan terbentuklah hormogonium.
• Anggota ordo ini adalah:
a) Familia Oscilatoriaceae
- Hidup dalam air atau di atas tanah basah.
- Bentuk sel bulat dengan sudut persegi.
- Dapat membentuk koloni benang, dan dinding sel mengeluarkan lendir.
- Pada jarak tertentu pada benang terdapat sel-sel yang dindingnya tebal, berwarna kekuningan (hilang kromatofornya), disebut heterosista. Heterosista dapat tumbuh menjadi benang yang baru, fungsinya belum jelas, biasanya lekas mati.
- Contoh: Oscillatoria linosa, O. princeps.

b) Familia Rivulariaceae
- Membentuk percabangan yang banyak.
- Pangkalnya terdiri atas suatu heterosista, ujungnya berambut.
- Contoh: Rivularia bullata, R. haematites.

c) Familia Nostotaceae
- Sel bulat memenjang dengan ujung membulat, terbentuk heterosista dan akinet (sel berisi klorofil) di sebagian besar selnya.
- Dapat menambat N dari udara, seringkali bersimbiosis dengan Fungi dan Lichenes.
- Contoh: Nostoc commune, N. sphaeroides, Anabaena cycaeae ( bersimbiosis dengan pakis haji/Cycas rumphii dalam akar-akarnya yang berbentuk seperti bunga karang), A. azollae (bersimbiosis dengan Azolla pinnata sejenis paku air, dalam daunnya yang hidup di sawah atau di rawa).

Daftar Pustaka
Brock, T.D. dan M.T. Madigan. 1991. Biology of Microorganisma. Prentice Hall, Inc. USA.
Kimball, J.W. 1992. Biologi. Jilid 3. Erlangga. Jakarta.
Scheeler, P. dan D.E. Bianchi. 1987. Cell and Molecular Biology. John Wiley & Sons, Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
Smith, G.M. 1965. Cryptogamic Botany (Schizophyta and Thallophyta). Mc Graw-Hill, Inc. New York.
Tjirosoepomo, G. 1998. Taksonomi Tumbuhan: Schizophyta, Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
sumber: Hasnunidah, Neni. 2007. Botani Tumbuhan Rendah. Unila. Bandarlampung.