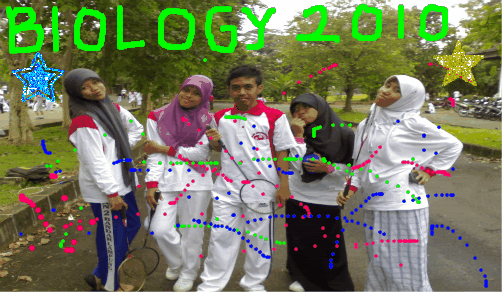Beberapa tokoh yang ikut memperkembangkan biologi sel adalah:
· Marcello Malpighi (1628-1694), seorang ilmiawan dan dokter Italia, mempelajari struktur-struktur tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, dan menamakan sel-sel “globulus”. Dialah yang dianggap sebagai “bapak anatomi mikroskopi”, dan menemukan adanya kapiler-kapiler darah, yang kira-kira 30 tahun sebelumnya sudah diperkirakan adanya oleh William Harvey.
· Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), seorang ahli mikroskop dari negeri Belanda, mempelajari struktur seluler tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, termasuk bacteria, protozoa dan spermatozoa.
· Robert Hooke (1635-1703) dari Inggris, mempelajari struktur-struktur mikroskopis dan mengemukakan berbagai tipe-tipe objek alami, dan pada waktu penelitiannya dari jaringan gabus tumbuh-tumbuhan, ia melihat adanya struktur-struktur yang sangat kecil berbentuk kotak-kotak, yang disebutnya sebagai “cel”.
· Nehmiah Grew (1641-1712) seorang dokter Inggris juga mempelajari struktur-struktur mikroskopis dan mengarang dari hal cel-cel dan jaringan pada tumbuh-tumbuhan (1672). Bersama-sama dengan Malpighi kemudian ia meneliti selanjutnya struktur mikroskopis tumbuh-tumbuhan sedemikian rupa baiknya sehingga selama lebih dari satu abad pengetahuan dari hal itu mengalami penambahan.
· Robert Brown (1773-1858) seorang Scotlandia, menemukan nukleus di dalam sel-sel tumbuh-tumbuhan pada umumnya (1831).
· Matthias Schleiden (1804-1881) seorang ahli botani Jerman, dan Theodor Schwann (1810-1882) mempelajari struktur-struktur mikroskopis pada berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan dan selanjutnya mengarang “prinsip-prinsip sel” (1839) dimana diterangkan bahwa organisme-organisme hidup tersusun dari sel-sel, atau sel-sel dengan hasil-hasilnya. Meskipun mereka ini secara umum telah diakui, Rene Dutrochet (1776-1847) seorang ahli fisiologi Perancis ternyata mendahuluinya dengan pandangan yang serupa (1824). Ia menyatakan bahwa pertumbuhan di sebabkan baik oleh pertambahan “volume sel-sel maupun adanya sel-sel kecil yang baru”.
· Edmund B. Wilson (1856-1939) seorang ahli Cytologi Amerika, mengarang buku : “ The Cell in Development and Heredity” (1924). Ia memusatkan perhatian kepada penelitian sel serta berusaha menerangkan fenomena biologis.
TERJADINYA TEORI SEL
Teori sel bersama-sama dengan teori evolusi merupakan dasar yang utama dari biologi modern. Antara teori tersebut ada banyak persamaan antara lain oleh karena teori-teori tersebut terwujud dalam suatu bentuk yang definitif pada suatu waktu yang hampir bersamaan, dan keduanya telah mengalami perkembangan selama suatu periode yang panjang. Dalam perkembangan biologi dewasa ini kedua teori tersebut hampir tidak dapat dipisahkan.
Sel adalah suatu satuan dasar dari kehidupan, yakni merupakan suatu satuan terkecil dari suatu benda yang kita nyatakan hidup. Hal ini dinyatakan oleh Theodor Schwann dengan jelas, bahwa semua organism hidup, baik yang bersel tunggal maupun yang tersusun dari kelompok-kelompok sel, tersusun dari sel-sel (1839).
Tidak ada suatu kehidupanpun yang terpisah dari kehidupan sel-sel. Bahkan organisme-organisme yang besar dan kompleks seperti misalnya manusia atau sebatang pohon raksasa. Setiap bagian yang khusus dari organisme, seperti kulit, tulang, otot, saraf, dan bahkan darah, ataupun kayu, bunga, akar, tersusun dari sel-sel khusus dengan variasi-variasi tambahan yang khas pula dari material-material interseluler yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut.
Pernyataan Schwann tersebut dilandasi oleh suatu proses yang dikemukakan oleh Rudolf von Virchow dalam pernyataan kemudian yang berbunya:” semua sel hanya timbul /berasal dari sel-sel yang telah ada terlebih dahulu” (1858).
Pernyataan Virchow ini selanjutnya ternyata sesuai dengan hasil penelitian Louis Pasteur (1822-1895) yang dilakukannya dalam tahun 1959-1861, yang membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu benda hiduppun yang tidak berasal dari benda hidup yang lain. Di samping itu pernyataan Virchow sejalan pula dengan Teori Evolusi dari Darwin yang dikemukakan pada tahun 1859.
Penelitian-penelitian Pasteur ini telah mengakhiri keyakinan mengenai teori “generatio spontanea” yang berabad-abad sebelumnya diakui sejak Aristoteles (384-322 sebelum Isa) menyatakan bahwa lalat dan nyamuk timbul dari benda-benda yang membusuk, yang telah mulai disangkal oleh Francesco Redi (1627-1697) dengan pembuktiannya yang manyatakan bahwa ulat-ulat tidak mungkin timbul dari daging yang membusuk apabila tidak ada peletakan telur sebelumnya oleh lalat-lalat pada daging tersebut.
Berdasarkan hasil penelitiannyatersebut, Pasteur mengemukakan keyakinan terhadap prinsip “biogenesis”, yang menyatakan bahwa “semua kehidupan berasal dari kehidupan yang lain”.
Hubungan antara Teori sel dan evolusi tercakup di dalam pernyataan Virchow: “…untuk seluruh rangkaian/urut-urutan bentuk-bentuk kehidupan, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan ataupun bagian-bagian penyusunnya berlaku suatu hokum yang abadi dari perkembangan yang terus menerus berlangsung.
Dalam hal ini Virchow melihat adanya suatu kelangsungan yang tidak pernah terputus dari generasi-generasi sel yang berurutan dan tampaknya tak pernah berakhir, yang ternyata kembali ke asal-usul kehidupan. Dengan demikian, dengan terbuktinya bahwa semua sel berasal dari sel-sel lain, didapatkan suatu pengertian bahwa semua sel mempunyai asal-usul yang sama.
Pendapat Schwann yang menyatakan bahwa semua organisme tersusun dari bagian-bagian yang pada dasarnya sama yang disebut sel, mengingatkan kita pada pendapat Comte de Buffon (1707-1788) yang mengemukakan adanya berbagai persamaan structural pada vertebrata. Kedua pengertian tersebut dapat dijelaskan oleh teori evolusi. Hewan-hewan yang termasuk vertebrata, tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada, mempunyai suatu keseragaman dalam suatu pola structural tertentu, oleh karena hewan-hewan tersebut mempunyai asal-usul yang sama. Demikian pula, semua sel-sel hidup, tanpa memandang adanya perbedaan-perbedaan yang dijumpai, dalam suatu pola yang sama menunjukkan adanya persamaan structural yang membuktikan bahwa sel-sel tersebut mempunyai suatu persamaan asal di dalam kehidupan awal yang silam.
Baik di dalam sel-sel maupun organisme-organisme, berbagai pembaharuan dan variasi yang timbul bersama dengan kemajuan evolusi tidak akan dapat mengaburkan batas-batas bentuk-bentuk yang telah diwariskan dari nenek moyangnya.
Peralihan dari pernyataan-pernyataan Hooke dan Leeuwenhoek ke pernyataan Schwann merupakan peralihan dari suatu hasil penelitian yang sederhana terhadap fakta yang dijumpai, ke suatu pernyataan yang timbul akibat induksi, yang jauh lebih luas. Sedangkan peralihan dan pernyataan Schwann ke pernyataan Virchow merupakan peralihan dari suatu pernyataan yang sederhana menjadi suatu teori, yang menjelaskan pernyataan tersebut.
Kesukaran-kesukaran yang menghambat/memperlambat terbentuknya prinsip-prinsip sel pada saat itu antara lain meliputi:
1) tidak/belum adanya alat-alat penelitian untuk mempelajari sel-sel secara efektif.
2) ilmu eksakta eksperimental seperti yang kita lakukan saat ini belum umum digunakan.
3) para ahli biologi pada saat itu lebih mengutamakan anatomi makroskopis, sehingga pengetahuan mikroskopis yang mendalam dianggap tidak begitu perlu.
4) meningkatnya perhatian terhadap perkembangan embrional dari organisme-organisme yang timbul pada awal abaditu membelokkan perhatian dari aspek-aspek makroskopis kearah penelitian-penelitian yang mendalam terhadap sel-sel dan organisasi yang bersangkutan.
5) teknik-teknik pewarnaan belum digunakan secara ekstensif sehingga banyak struktur-struktur sel yang belum terlihat.
6) metode-metode pemotongan dari jaringan-jaringan yang diperlukan untuk mempelajari detail-detail seluler belum digunakan pada waktu itu.
Sel-sel memang sukar dipelajari, oleh karena sel-sel bersifat jernih, sensitive (irritable) dan sangat halus. Di dalam sel-sel terdapat organisasi yang teratur, dengan susunan-susunan yang dinamis dan interaksi di antara komponen-komponen kimiawinya yang semuanya penting bagi tiap-tiap sel, karena adanya bermacam-macam komponen di situ. Dalam hal ini, organisasi alami, yang dimiliki oleh sel-sel tersebut mungkin berubah dengan adanya prosedur-prosedur yang dipakai pada waktu mempelajari sel-sel, sehingga menghasilkan informasi yang tidak begitu lengkap mengenai struktur dan fungsi yang sebenarnya dari komponen-komponen penyusunnya.
Organisasi Sel
Sel adalah organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Beberapa ahli biologi menyatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel yang terkecil, yang disebut virus, yang dikenal sebagai penyebab-penyebab penyakit seperti infuluenza, polio-myelitus dan pneumonia.
Berbagai jenis virus tersebut hidupnya sama sekali tergantung pada sel-sel hidup. Apabila suatu virus menyerang sel-sel hidup dari organisme maka virus tersebut akan menyebabkan terhentinya aktivitas-aktivitas mekanis dari sel hospes dan menghasilkan virus-virus yang baru. Dengan demikian dalam hal ini sel hospes tersebut dihancurkan. Reproduksi virus tidak dapat dipandang sebagai reproduksi sendiri oleh karena reproduksi tersebut hanya dapat berlangsung melalui mekanisme-mekanisme sel-sel hospes. Dengan demikian keadaan hidup yang tersebut pada virus adalah cukup beralasan untuk diragukan oleh karena “reproduksi sendiri” merupakan salah satu tanda karakteristik yang utama dari suatu sistem kehidupan, seperti juga halnya pengaturan sendiri, yang kedua-duanya tidak dipunyai oleh virus yang berada dalam suatu keadaan bebas.
Setiap sel merupakan organisasi material minimal yang mampu melakukan proses-proses yang secara kolektif tersebut “hidup”. Dalam ketentuan ini harus diingat bahwa definisi ini hanya berlaku di dalam alam yang sudah maju seperti sekarang ini, oleh karena kita masih tetap meyakini bahwa kehidupan muncul pertama-tama sekali berjuta-juta tahun yang lalu dari suatu yang tidak hidup, dalam suatu bentuk tertentu yang jauh lebih sederhana dari keadaan sel yang kita kenal saat ini.
Apabila kita perhatikan beberapa sel tampak jelas adanya tingkatan-tingkatan organisasi dan kompleksitas yang sudah sangat tinggi apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang setingkat lebih maju dibandingkan dengan benda-benda yang tak hidup.
Organisasi-organisasi preseluler dari bentuk-bentuk yang menuju kea rah organisme hidup tidak dapat bertahan hidup lama oleh karena pertama-tama keadaan lingkungan telah berubah sama sekali dari keadaan lingkungan sejak mulainya kehidupan pertama-tama, sehingga kondisi-kondisi lingkungan yang memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk preseluler dari kehidupan juga telah lama lewat; kedua, telah terbentuknya sistem-sistem reproduksi yang lebih efisien dan maju, sebagai suatu aspek evolusi organic yang universal.
Sel yang sebagaimana kita kenal saat ini merupakan suatu organisasi yang terjadi secara berangsur-angsur dan bertingkat kea rah bentuk yang lebih maju, dari bentuk-bentuk di dalam mana proses-proses dasar yang karakteristik bagi kehidupan berlangsung secara tepat dan pasti. Perkembangan ini tentu saja berlangsung pada suatu jangka waktu yang sangat panjang, mungkin lebih dari satu juta tahun yang menggantikan transisi-transisi preseluler yang belum “masak” yang berada di antara benda-benda yang hidup dan tidak hidup.
Adanya kehidupan preseluler tentu saja jangan sampai mengaburkan kita terhadap arti pernyataan mengenai kehidupan saat ini, karena bagaimanapun juga, sel adalah satuan terkecil dari kehidupan. Baik di dalam sel maupun hubungan-hubungannya dengan sel-sel yang lain, kita harus dapat menemukan adanya organisasi-organisasi yang menjadi dasar bagi semua proses-proses kehidupan, seperti: pengambilan, penimbunan dan pelepasan energi, pengambilan material-material dan metabolismenya yang menuju ke pertumbuhan; penerimaan dan reaksi terhadap stimuli;pergerakan; dan proses kehidupan yang paling utama, reproduksi.

Sel adalah:
1) Satuan structural yang terkecil dari hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jaringan-jaringan dan organ-organ yang tersusun dari sel-sel, serupa dengan sebuah batu bata sebagai suatu satuan structural dari suatu dinding batu.
2) Satuan fungsional/fisiologi yang terkecil, karena fungsi-fungsi dari organisme-organisme hidup merupakan akibat dari aktivitas-aktivitas seluler dari organisme-organisme tersebut. Tiap-tiap sel bekerja sebagai suatu satuan, tetapi kebanyakan kelompokan-kelompokan sel bekerja bersama untuk suatu tujuan yang sama. Dalam hal semacam ini selalu dijumpai adanya saling bergantung satu dari yang lain, interfungsi, koordinasi dan subordinasi, apabila organisme tersebut berfungsi sebagai suatu kesatuan dengan efisien.
3) Satuan pertumbuhan dan perkembangan yang terkecil karena sekalipun suatu organisme yang kompleks, dengan sejumlah besar sel-sel, tumbuh dan berkembang melalui suatu proses pembelahan dari sel-selnya, pertumbuhan serta perkembangan sel-sel menyusun organisme tersebut.
4) Satuan factor herediter yang terkecil, karena melalui sel-sel itulah material-material herediter diterima dari induk-induknya, dipertahankan di dalam embrio dan bentuk dewasa untuk kelak diturunkan kepada keturunannya. Selama pembelahan faktor-faktor tersebut juga harus selalu tetap dalam keadaan seperti yang terwaris, sebab apabila tidak, akan kehilangan sifat-sifatnya semula.
5) Satuan regenerasi yang terkecil, sebab apabila sesuatu jaringan diganti atau diperbaiki, sel-selnya itulah yang memegang peranan utama di dalam mencapai tujuan tersebut. Apabila sel-sel di dalam hal ini bekerja abnormal, sudah barang tentustruktur-struktur yang abnormal pulalah yang akan terbentuk. Dalam keadaan semacam inilah timbul pendapat bahwa pertumbuhan-pertumbuhan semacam tumor dan kanker disebabkan oleh pembelahan-pembelahan sel yang abnormal.
Ukuran dan Bentuk Sel
Ukuran sel pada umumnya bersifat mikroskopis. Pada manusia, diameter rata-rata dari sel-selnya kira-kira 10 mikron atau 0,01 mm.
Suatu sel bakteri, berdiameter ± 0,4 mikron, hampir-hampir tidak teramati dengan suatu mikroskop biasa. Ukuran sel-sel lainnya pada umumnya berkisar pada ukuran-ukuran tersebut, tentu saja dengan beberapa perkecualian pada sel-sel tertentu.
Misalnya pada seekor hewan yang besar, suatu sel saraf dapat mencapai panjang lebih dari 1 meter, meskipun diameternya relative kecil.
Pada hewan-hewan, ova (sel-sel telur) yang belum memulai perkembangannya, merupakan sel-sel tunggal yang biasanya dapat terlihat dengan mata biasa. Misalnya sel telur manusia, tanpa bantuan sesuatu lensa dapat kita lihat kira-kira sebesar titik (.). sedangkan sel telur dari seekor jenis burung yang telah punah (Alpyornis dari Madagaskar), bahkan berkapasitas sampai lebih dari 4 gallon, dan merupakan sel telur yang bervolume terbesar di antara sel-sel telur jenis hewan apapun. Pada telur burung, yang disebut selnya sesungguhnya adalah vitellusnya, dan membesarnya telur adalah disebabkan oleh adanya material makanan yang dikelilingi oleh material tambahan yang lain, yang biasanya kita kenal sebagai putih telur dan kulit telur. Dengan demikian mengenai ukuran rata-rata dari sel-sel adalah sangat sukar untuk ditentukan secara pasti. Pada table berikut diberikan beberapa ukuran-ukuran sel tertentu sebagai berikut:
Objek | Diameter | |
µ | Å | |
Ovum manusia | 100 | 1000.000 |
Erythocyt | 10 | 100.000 |
Bacterium | 1 | 10.000 |
virus | 0,1 | 1000 |
Mengenai bentuk-bentuk sel juga terdapat variasi yang tidak terbatas, yang terutama bersangkutan dengan fungsi-fungsi khususnya di dalam suatu organisme secara keseluruhan. Adanya suatu tendensi kea rah bentuk umum dari sel-sel, biasanya berupa tendensi kea rah bentuk spheris.
Berbagai variasi bentuk dari sel misalnya:
- Pipih seperti lempeng, sebagai contoh misalnya pada kulit (integumentum)manusia.
- Memanjang, misalnya pada sel-sel otot.
- Bikonkaf dan berbentuk difus misalnya pada sel-sel darah.
- Sangat memanjang, sesuai dengan fungsinya sebagai penghantar impuls-impuls, misalnya pada sel-sel saraf.
Sumber:
Radiopoetro. 1996. Zologi. Erlangga. Jakarta